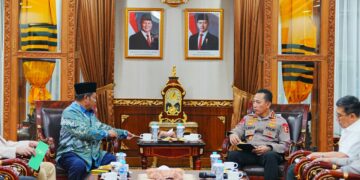SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Dunia lagi panas-panasnya. Bukan cuma cuaca, tapi juga urusan ekonomi. Dan kali ini, Indonesia kembali jadi korban “drama internasional” dari negara adidaya yang seolah-olah selalu benar: Amerika Serikat.
Kebijakan terbaru AS menjatuhkan tarif tinggi—bahkan sampai 47%—untuk produk-produk ekspor unggulan Indonesia seperti garmen, sepatu, dan tekstil. Buat mereka, ini mungkin strategi. Tapi buat kita? Ini bom waktu yang bisa meledak di tengah-tengah perut rakyat kecil.
Padahal jauh sebelum istilah globalisasi dipopulerkan, Nusantara sudah mengenal nilai perdagangan bebas dan adil. Sultan Alauddin dari Makassar, pada abad ke-16, pernah berkata, “Tuhan menciptakan bumi dan lautan. Bumi Dia bagi-bagikan di antara manusia, dan laut Dia berikan untuk dimiliki bersama. Tidak pernah terdengar bahwa seseorang harus dilarang berlayar di lautan.” Pernyataan ini, yang dikutip dalam buku sejarah karya Anthony Reid dan Philip Bowring, seakan menampar kita hari ini. Dulu kita berdaulat. Sekarang?
Dampak dari tarif ini bukan sekadar angka di atas kertas. Menurut data Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sebanyak 1,2 juta pekerja Indonesia terancam kehilangan pekerjaan. Industri tekstil dan produk tekstil paling terdampak, dengan lebih dari 191.000 pekerja siap-siap jadi korban PHK. Lalu disusul oleh sektor makanan, minuman, bahkan para petani yang memasok bahan baku.
Yang lebih menyakitkan? Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mencoba bertindak. Pada 14 April 2025, delegasi yang terdiri dari Menlu Retno Marsudi, Menko Airlangga Hartarto, dan Menkeu Sri Mulyani terbang ke AS untuk bernegosiasi. Tapi hasilnya? Tidak membuahkan kabar gembira. Bahasa halusnya: progres, tapi belum konkret. Bahasa kasarnya: zonk.
Dan ketika para elite sibuk dalam rapat tertutup dan diplomasi panjang, rakyat bawah berteriak dari garis depan. Dalam rapat Komite III DPD RI seminggu sebelum Hari Buruh, perwakilan serikat buruh dari seluruh Indonesia menyampaikan keluhan mereka: takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan masa depan. Tapi suara mereka masih seperti gema di ruangan kosong.
Yang sering luput dari sorotan adalah sektor informal. Padahal mereka ini tulang punggung sejati ekonomi Indonesia. Mulai dari pedagang kaki lima, penjahit rumahan, reseller produk lokal—semuanya rentan kena getahnya. Sayangnya, perhatian pemerintah untuk mereka? Minim, nyaris tak terdengar.
Kini, pertanyaannya semakin tajam: apakah pemerintah masih punya arah? Atau kita semua hanya jadi penonton dalam sinetron geopolitik yang tak pernah menguntungkan negara berkembang? Negosiasi demi negosiasi sudah dilakukan, tapi kenyataannya rakyat belum merasakan hasilnya.
Sudah saatnya kita bicara soal kedaulatan. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan kebijakan, dan kedaulatan rakyat untuk tidak terus-terusan menjadi korban kepentingan negara besar. Cukup jadi objek. Kini saatnya jadi subjek.
Kita punya sejarah panjang sebagai bangsa maritim yang terbuka, toleran, dan cerdas berdagang. Semangat itu harus kembali dihidupkan. Bukan untuk nostalgia semata, tapi untuk menyelamatkan masa depan.
(Anton)