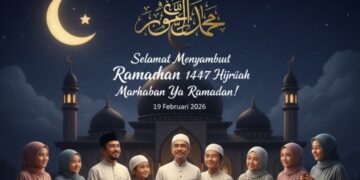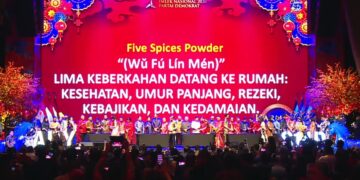SUARAINDONEWS.COM, Surakarta-Karya seni rupa yang terinspirasi oleh ‘sesuatu’ (ekspresi budaya) yang tradisional’ semakin sering kita saksikan. Penggambarannya seperti dua kalimat pendek dari esai ringkas Goenawan Mohamad (GM) yang ditujukan sebagai tanggapan untuk S. Takdir Alisjahbana, yakni “Residu kebudayaan lama ternyata tetap menebal. Tradisi tak mati-mati”.
Seperti juga Esai berjudul Beberapa Tusuk Sate dan Segelas Rum. Esai itu mengurai perkara sate yang enak dan lezat, dibakar di atas alat/plat yang sudah lama dan berselaput lemak; karena ketika proses membakar, bumbu-bumbu yang menempel pada plat berlemak itu ikut terserap. Demikian pun bir yang nikmat, berasal dari drum lama yang sudah berkerak; karena rasa bir baru berpadu dengan kerak bir lama.
Seperti filosofi kuliner orang Jawa yang menyebutnya dengan rasa masakan dengan “mirasa”. Kira-kira bermakna bumbu-bumbunya terserap dalam keseluruhan masakan itu, hingga meninggalkan jejak rasa di lidah. Dalam konteks gamelan, apakah “benda” dan “bunyi” yang terus dikreasi itu menunjukkan jejak residu dan “kelezatan” baru? Apakah juga memproduksi pengetahuan baru? Atau setidaknya menghadirkan sensasi baru?
Demikinlah memandang dan menghayati ‘gamelan’ dengan segenap bunyi yang digubah oleh para pencintanya. Gamelan merupakan artefak budaya tradisional yang terus diproduksi ‘bendanya’, terus dikreasi ‘bunyinya’, dan terus dihidupkan oleh berbagai komunitas di banyak negara di dunia.
Pameran Serupa Bunyi salah satu agenda dari perayaan International Gamelan Festival 2018, yang akan berlangsung pada pada 10-15 Agustus 2018 merupakan hasil kerja sama Galeri Nasional Indonesia dengan Taman Budaya Jawa Tengah, menawarkan Petualangan Estetik Rupa-Bunyi. Pameran yang berfokus pada karya seni rupa kontemporer yang menempatkan gamelan sebagai sumber penciptaannya baik oleh Heri Dono, Hanafi, Nindityo Adipurnomo, Edwin Rahardjo, dan Hajar Satoto (alm.), menggubah karya-karyanya yang bertautan dengan gamelan. Mari kita lihat dari dekat karya-karya mereka.
Gamelan, salah satu artefak seni tradisional, merupakan “sumber tanpa batas” untuk direspon oleh para seniman dengan/dan untuk atas nama apa pun: untuk rekreasi, revitalisasi, inspirasi, dan lain-lainnya. Kesemuanya membuktikan, bahwa gamelan tak akan pernah mati, rembaka, dan terus menemukan konteks dan kehidupannya yang lain.
Seperti karya instalasi Gamelan Goro-Goro (440 x 320 x 200 cm; 2001) Heri Dono yang menghasilkan bunyi yang menarasikan situasi kasak-kusuk. Elemen air dalam karya ini dapat kita baca sebagai ujung dari peristiwa goro-goro, yakni terkuaknya kebusukan, dan menghasilkan tatanan dunia baru yang dipenuhi keteraturan serta ketertiban. Sedangkan karya Heri lainnya Shock Therapy for Global Political Leaders (31 x 31 x 150 cm terdiri atas 10 pcs; instalasi dinding); yang bertolak dari isu politik internasional, seperti ketegangan baru pasca-Perang Dingin, upaya penghancuran Irak, Afghanistan, Libya, terorisme 911 di Amerika Serikat, Brexit, dan yang terbaru (meski lama) adalah ketegangan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara, dan dengan Rusia.
Benih Bunyi ‘Perupa Hanafi’ adalah dampak, entah karena gesekan, petikan, atau pukulan. Maka apa yang terdengar dan terasa bisa berbeda, tergantung dari siapa pembuat bunyi dan pendengarnya. Bunyi juga dapat mengakibatkan sesuatu. Bunyi merupakan persoalan cita rasa. Hanafi meresapi dan mewujudkannya dalam Metaforis, Delapan Benih Bunyi, berjajar delapan lukisan (delapan panel lukisan, acrylic pada kanvas, 2018); karya keempat berukuran lebih besar (lebih tinggi dan lebih lebar) menggubah citraan laki-laki Jawa (berbusana tradisional Jawa; mengenakan blangkon, surjan, berkain, dan terselip keris bergaya ladrang di pinggangnya). Dari gestur tubuh yang dilukiskan dari belakang itu, laki-laki ini berperan sebagai konduktor orkestrasi; tangan kiri terangkat lebih tinggi, tangan kanan memegang stik, sebuah gestur untuk memberikan aba-aba bunyi.
Begitu dengan karya Nindityo Adipurnomo yang Menyusuri Bunyi Tersembunyi
Toa, lewat Gamelan Toa (instalasi patung-patung batu, bendera batik, dan tikar sajadah; 500 x 300 x 250 cm; 2018) – berupa bentuk instrumen kempul (dalam rumpun bonang) terbuat dari batu, mengisyaratkan makna paradoks, sekaligus ajakan untuk mundur sejenak, merenungi (juga memaknai) untuk melihat perjalanan peradaban kita.
Sementara Edwin Raharjo Merayakan Perbedaan dengan karya bertajuk Harmony in Diversity (gender, base, gunungan, kenong, duralium, brass, kulit, program solenoid, servo, motor; 2015), menyodorkan kesan glamour; mereka rakit gamelan dengan pukulnya, menjadi gerak kinetik yang menghasilkan bunyi. Seluruh gerak dikendalikan oleh teknologi digital. Mungkin karena Edwin berjarak dengan tradisi gamelan, maka bunyi yang dihasilkan tidak dihasratkan sebagai sebuah komposisi orkestrasi bunyi. Tetapi sekadar sebagai bunyi.
Edwin juga menghadirkan citra wayang kulit, dengan pendar-pendar cahaya bergantian, yang ditata secara instalatif di dinding. Karya ini memuat spirit baru, mewakili gairah dan pesona terhadap teknologi informasi. Tanpa kemampuan mereka-rakit (menginstalasi) menggunakan teknologi tinggi (termasuk digital), akan kesulitan menghadirkan sajian yang sempurna. Edwin Raharjo memulai mengolah seni tradisional ini dengan pendekatan teknologi tinggi dan menyodorkan kesan mewah.
Sedangkan Bilah Pamor Hajar Satoto, almarhum, lulusan Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia (STSRI) “ASRI” Yogyakarta menamai garapannya dengan sebutan Gamelan Pamor (seluruh perangkat gamelan ia garap ulang, dengan besi berpamor). Secara visual karyanya menggetarkan; bilah-bilah gamelan hasil dari tempaan dan olahan berbagai benih besi, yang melahirkan pamor – atau motif – di sekujur bilah. Hajar Satoto merakit kembali bilah-bilah berpamor itu dalam bentuk seperti gamelan aslinya. Karya Gamelan Pamor Hajar Satoto memukau dan menggetarkan. Setiap bilah, setiap bentuk instrumen gamelan, terdiri atas relung-relung motif (pamor) yang menantang mata untuk mendekati.
Kepala Galeri Nasional Indonesia, Pustanto, menegaskan bahwa melalui Pameran Seni Rupa Kontemporer “Serupa Bunyi”, Galeri Nasional Indonesia kembali melaksanakan platform kebudayaan yang mengintegrasikan kegiatan Galeri Nasional Indonesia dengan daerah di luar Jakarta, dalam hal ini mendukung/bersinergi dengan International Gamelan Festival (IGF) 2018 sebagai rangkaian kegiatan Indonesiana yang digelar sepanjang bulan Juli-Oktober 2018 di beberapa wilayah di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi pemerintah setempat.
Seperti diketahui Galeri Nasional Indonesia sebelumnya telah beberapa kali menjalankan program dukungan/sinergi antarlembaga budaya. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, program tersebut dilaksanakan dalam bentuk Pameran Seni Rupa Internasional Biennale Terracotta 1st di Yogyakarta (2015), Workshop Melukis Mural dalam rangka Temu Karya Taman Budaya (TKTB) se-Indonesia di Kupang (2015), Workshop Seni Lukis dalam rangka mendukung ajang Pra–Biennale 2015 di Makassar (2015), Workshop Seni Lukis “Tips & Trik Melukis Model” dalam rangka mendukung Pekan Budaya Indonesia (PBI) #2 di Malang-Jawa Timur (2016), dan “Workshop Melukis di Atas T-Shirt” di Palu- Sulawesi Tengah dalam rangka mendukung Pekan Budaya Indonesia (PBI) #3 (2017).
Dan melalui Pameran “Serupa Bunyi”, kami berharap semoga dapat memberikan sajian yang inspiratif, edukatif, dan rekreatif bagi publik luas, khususnya masyarakat yang berada di Solo dan sekitarnya baik pelajar, mahasiswa, pendidik/pengajar seni budaya, komunitas seni, maupun masyarakat umum, tambahnya.
Karya-karya mereka menghadirkan pengalaman baru, bagi dirinya, maupun bagi orang lain, terkait dengan pengertian, pemahaman, atau penghayatan terhadap seni tradisi. Mereka melalui karya seni rupa, dengan caranya, dapat dipahami sebagai upaya merawat dan menghidupkan kebudayaan, jelas kurator Suwarno Wisetrotomo.
Indonesiana adalah platform pendukung kegiatan seni budaya di Indonesia yang bertujuan untuk membantu tata kelola kegiatan seni budaya yang berkelanjutan, berjejaring, dan berkembang. Indonesiana diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan semangat gotong royong dan melibatkan semua pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan atas pemajuan kebudayaan di Indonesia. Kegiatan ini sejalan dengan disahkannya UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang kemudian memunculkan kebutuhan untuk menangani kegiatan budaya secara lebih sistematis.
Pada tahun pertama (2018), Indonesiana akan melakukan pendukungan untuk 9 festival seni budaya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan melibatkan pemerintah daerah, komunitas, pusat kebudayaan/kedutaan asing serta swasta dalam berbagai bentuk kolaborasi. 9 festival tersebut antara lain Festival Vula Dongga, Festival Palu Salonde Percussion, Festival Bunyi Bungi, Cerita dari Blora, Festival Seni Multatuli, Festival Budaya Saman, Festival Tenun Nusantara, Festival Fulan Fehan, Silek Arts Festival, Bebunyian Sintuvu Sulawesi Tengah, dan International Gamelan Festival (IGF). Sedangkan International Gamelan Festival (IGF) sendiri merupakan festival berskala internasional yang dihelat pada salah satu lokus terpenting yang bertujuan untuk menciptakan arena mudik atau “homecoming” bagi kelompok-kelompok gamelan yang telah menyebar ke berbagai belahan dunia dan dalam beraneka corak perkembangan dan fungsinta.
(tjo ; foto ist