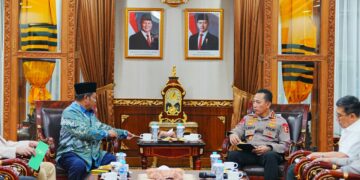SUARAINDONEWS. COM, Jakarta — Banjir yang terus berulang di berbagai daerah dinilai bukan semata persoalan curah hujan, melainkan cerminan kegagalan manusia dalam mengelola air dan menata ruang hidupnya sendiri.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Sujatmiko dalam forum diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Atasi Bencana” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Menurut Sujatmiko, hujan sejatinya adalah anugerah alam yang seharusnya menopang keberlanjutan kehidupan. Namun, ketika tata ruang dan pembangunan berjalan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, air hujan justru berubah menjadi ancaman.
“Banjir itu bukan karena hujannya, tapi karena kita gagal mengelola air. Alam sudah memberi, tapi manusia tidak siap menerimanya,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini pengelolaan air masih bertumpu pada pendekatan darurat, bukan pencegahan. Padahal, air hujan seharusnya ditangani sejak awal, baik dengan menampungnya melalui bendungan dan waduk, maupun dengan memastikan air bisa kembali meresap ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah.
Sayangnya, pendekatan resapan air masih minim diterapkan. Permukaan tanah yang tertutup beton dan aspal membuat air langsung mengalir ke sungai, bahkan ke permukiman, tanpa sempat diserap. Kondisi inilah yang memperbesar risiko banjir, termasuk di wilayah yang sebelumnya relatif aman.
Sujatmiko juga mengingatkan bahwa hujan memiliki siklus alami dengan intensitas yang beragam, mulai dari lima tahunan hingga puluhan tahun. Tanpa pemahaman terhadap pola tersebut, pembangunan berisiko besar salah arah. Ia menilai, informasi teknis dari BMKG seharusnya menjadi rujukan utama dalam perencanaan wilayah.
“Kalau kita paham siklus alamnya, kita tidak akan sembarangan membangun di kawasan rawan,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti masih lemahnya kepatuhan terhadap tata ruang. Idealnya, ruang terbuka hijau dijaga minimal 40 persen, sementara sisanya baru dimanfaatkan untuk pembangunan. Namun, di banyak daerah, ketentuan ini kerap diabaikan.
Daerah aliran sungai (DAS) pun menjadi sorotan. Alih fungsi DAS menjadi kawasan permukiman dan komersial dinilai sebagai salah satu penyebab meluasnya banjir lintas wilayah.
“Kerusakan DAS itu efeknya tidak lokal. Bisa berdampak ke daerah lain yang jauh dari titik awal,” tegasnya.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramadhani menambahkan pentingnya pemanfaatan sistem early warning sebagai dasar tindakan cepat pemerintah daerah. Menurutnya, bencana hidrometeorologi memiliki golden time yang panjang, bahkan bisa terdeteksi hingga sepekan sebelumnya.
“Early warning harus diikuti early action. Informasi cuaca itu percuma kalau tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.
BMKG mencatat, pemanasan global membuat intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem terus meningkat. Karena itu, penguatan pemetaan risiko, rencana kontingensi, serta literasi kebencanaan di masyarakat menjadi keharusan.
Andri juga mengungkapkan bahwa wilayah selatan ekuator seperti Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara masih perlu waspada pada periode puncak musim hujan hingga masa transisi Maret dan April. Meski tren hujan mulai melandai, potensi cuaca ekstrem tetap bisa muncul akibat aktivitas bibit siklon tropis.
“Ancaman tidak berhenti di musim hujan. Kekeringan dan kebakaran hutan di musim kemarau juga perlu diantisipasi sejak dini,” katanya.
Baik Sujatmiko maupun BMKG sepakat, kunci pengurangan risiko bencana ada pada kolaborasi lintas sektor pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, hingga masyarakat. Tanpa pembenahan tata kelola lingkungan dan keseriusan menindaklanjuti peringatan dini, banjir dan bencana hidrometeorologi hanya akan terus berulang dari tahun ke tahun. (Kiki)
(Anton)