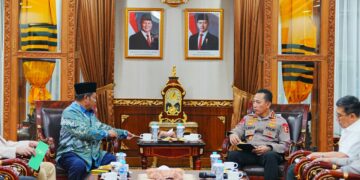SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Setiap 14 Februari, dunia tiba-tiba berubah warna. Merah di mana-mana. Mawar naik kelas. Cokelat mendadak jadi simbol kesetiaan. Restoran penuh. Dompet? Kosong perlahan.
Hari Valentine yang dulu dikaitkan dengan kisah Santo Valentinus—pendeta abad ketiga yang konon menikahkan pasangan secara rahasia pada masa Kekaisaran Romawi—kini telah berevolusi jauh melampaui romantisme klasik. Dari legenda eksekusi tahun 269 M hingga surat bertanda tangan “From Your Valentine”, perayaan ini berubah menjadi musim ekonomi global yang tak bisa diabaikan.
Dari Basilika San Valentino di Roma hingga Gereja Whitefriars di Dublin yang menyimpan relikui sang santo, sejarahnya panjang dan sakral. Tapi di era modern, yang paling sakral mungkin justru paket dinner couple 1,5 juta plus pajak.
Cinta Setahun Sekali, Sisanya Cicilan?
Bagi sebagian orang, Valentine adalah momen emas untuk “mengisi ulang” hubungan di tengah kesibukan. Namun bagi yang lain, ini sekadar tekanan sosial tahunan. Tidak sedikit generasi muda yang bertanya: apakah cinta benar-benar butuh tanggal khusus atau ini hanya deadline emosional yang diciptakan industri?
Jajak pendapat media internasional menunjukkan perpecahan jelas. Ada yang menolak konsep “cinta musiman” karena dianggap membatasi spontanitas. Ada pula yang melihat 14 Februari sebagai jeda penting dari rutinitas dan tekanan hidup modern.
Namun kritik paling keras datang dari sisi komersialisasi. Harga bunga melonjak. Restoran menaikkan tarif. Perhiasan dipasarkan sebagai bukti keseriusan hubungan. Tidak memberi hadiah? Siap-siap dicurigai.
Sebagian pengamat menyebutnya sebagai “komersialisasi perasaan”—ketika cinta bukan lagi ekspresi personal, melainkan kewajiban konsumsi.
Invasi Lembut atau Perayaan Universal?
Di beberapa komunitas religius dan pendukung identitas lokal, Valentine dianggap sebagai produk budaya Barat yang menyusup perlahan melalui simbol merah dan kartu romantis. Mereka menyebutnya “invasi lunak” terhadap nilai tradisional.
Namun generasi globalis, khususnya Gen Z, punya definisi berbeda. Bagi mereka, Valentine bukan cuma tentang pasangan. Ini tentang persahabatan, keluarga, bahkan self-love. Makan sendirian di restoran pada 14 Februari? Bukan menyedihkan, justru simbol kemandirian.
Data menunjukkan Gen Z semakin nyaman merayakan Valentine bersama teman atau dalam kelompok, bukan sekadar dinner romantis klasik. Konsepnya bergeser: dari eksklusif menjadi inklusif.
Musim Ekonomi Berkedok Romansa
Seiring berkembangnya percetakan dan kartu ucapan pada abad-abad sebelumnya, Valentine menjadi salah satu bentuk awal “komersialisasi perasaan.” Kini, skalanya jauh lebih besar.
Industri bunga, cokelat, perhiasan, restoran, hingga pariwisata memanfaatkan momen ini sebagai siklus ekonomi musiman. Strategi pemasaran membangun narasi bahwa hadiah adalah bahasa cinta. Tanpa hadiah? Seolah ada yang kurang.
Diskon edisi terbatas, paket makan malam romantis, perjalanan bertema cinta—semua dirancang untuk menciptakan urgensi emosional. Valentine bukan lagi sekadar tanggal, melainkan momentum bisnis yang setara dengan musim liburan besar.
Jadi, Siapa yang Diuntungkan?
Apakah Valentine adalah perayaan cinta yang tulus, atau jebakan mewah yang membuat kita merasa wajib membuktikan perasaan lewat transaksi?
Jawabannya mungkin tidak hitam putih. Di tengah kritik dan perdebatan, 14 Februari tetap menjadi ruang di mana manusia mencari koneksi, pengakuan, dan harapan—meski kadang dibungkus pita promosi dan harga spesial.
Pada akhirnya, mungkin bukan soal merayakan atau menolak Valentine. Tapi tentang memastikan bahwa cinta—apa pun bentuknya—tidak sepenuhnya ditentukan oleh etalase toko dan notifikasi diskon.
(Anton)